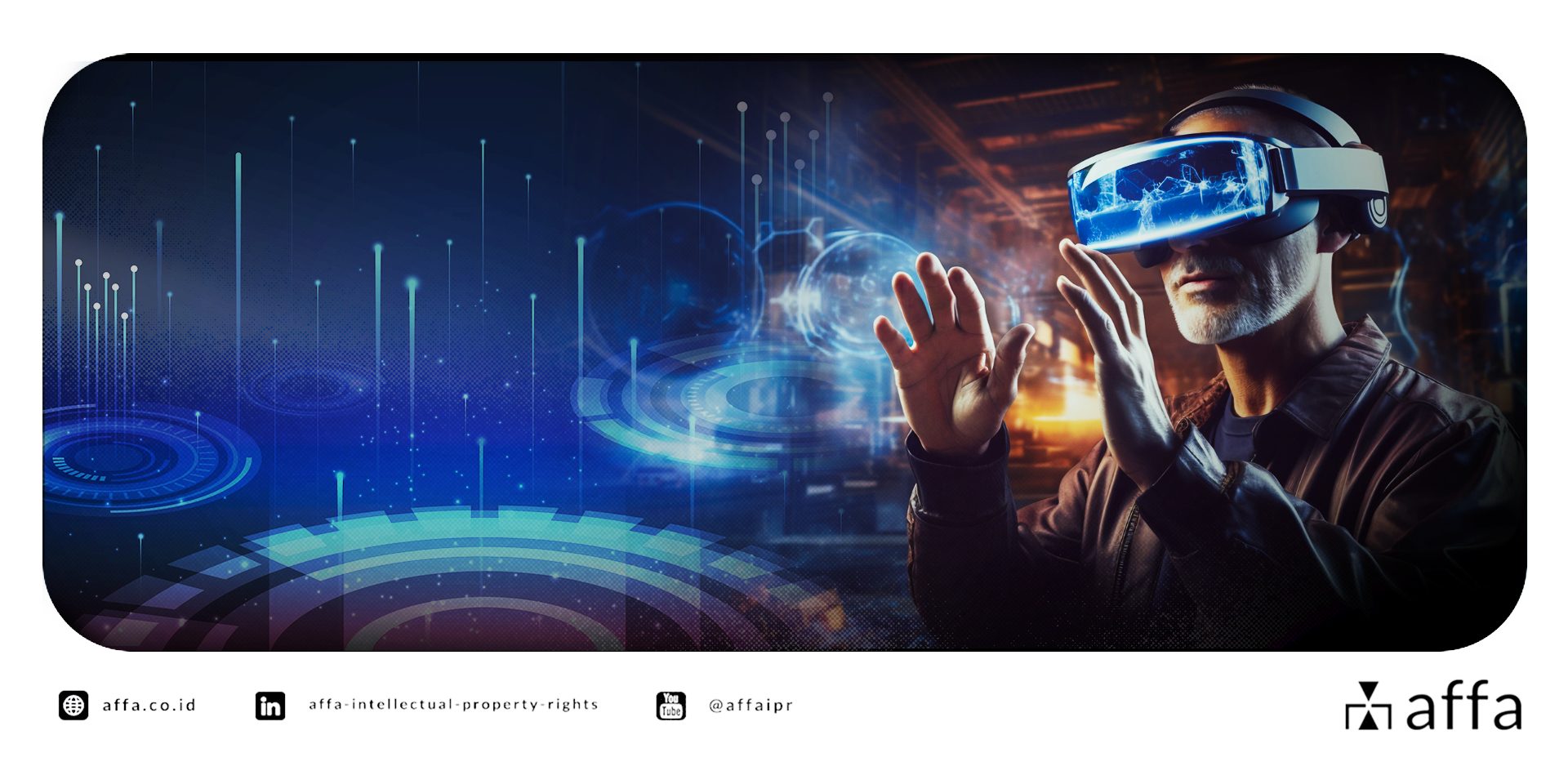Dalam beberapa tahun terakhir, percakapan global mengenai Paten telah bergeser dari sekadar membahas siapa yang menemukan lebih dulu menjadi siapa yang menciptakan standar. Di balik hadirnya 5G di ponsel kita, Wi-Fi di setiap sudut ruang publik, hingga USB-C yang kini menjadi port universal, terdapat satu istilah yang semakin mendominasi ruang diskusi Kekayaan Intelektual: Standard Essential Patents (SEP).
Isu ini tidak lagi sekadar berbicara tentang hak eksklusif, tetapi juga tentang akses terhadap teknologi dan tata kelola industri digital global.
Indonesia memang belum menjadi medan utama bagi sengketa SEP. Namun, beberapa perkara — seperti perselisihan terkait Paten Nokia di Pengadilan Niaga — mulai menunjukkan bahwa isu ini tidak lagi hanya milik Eropa atau Amerika Serikat.
Ketika suatu Paten telah diadopsi sebagai bagian dari standar teknis global, pertanyaannya tidak lagi sesederhana “siapa pemiliknya?”, melainkan “bagaimana lisensinya harus dibuka?” dan “apakah harus ada pembatasan berdasarkan kepentingan umum seperti dalam prinsip FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory)?”
Berbeda dari sengketa Paten di sektor farmasi atau life-sciences yang berfokus pada kebaruan atau domain publik, isu SEP membawa dimensi baru: standarisasi, akses, dan interoperabilitas. Sebuah Paten tidak hanya melindungi invensi, tetapi juga dapat menentukan siapa yang boleh masuk ke pasar — dan dengan syarat apa.
Kasus Terkait SEP Pertama di Indonesia
Kasus SEP pertama di Indonesia terjadi pada tahun 2015, melibatkan PT Polarchem, PT Garuda Tasco International, PT Star Metal Ware Industry, dan PT Golden Agin terhadap pemegang Paten IDS0001281.
Paten IDS0001281 merupakan Paten Sederhana (utility model) yang mengatur spesifikasi teknis alat sprayer, diajukan pada 31 Mei 2012. Paten ini memiliki kemiripan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan pada tahun 2018, yaitu SNI 8485:2018 mengenai alat penyemprot elektrik gendong beserta standar mutu dan metode pengujiannya.
Pemegang Paten keberatan atas pemberlakuan SNI tersebut dan tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan standar itu dalam produksi, serta tidak menyediakan lisensi. Sikap ini jelas bertentangan dengan konsep FRAND pada invensi yang telah dijadikan standar nasional.
Pemegang Paten sempat memenangkan perkara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Putusan No. 75/Pdt.Sus-Paten/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 30 Juni 2016). Namun, dalam tahap peninjauan kembali, Mahkamah Agung (Putusan No. 147 PK/Pdt.Sus-HKI/2018) menyatakan bahwa Paten IDS0001281 tidak memiliki kebaruan secara teknis, sehingga pendaftarannya dapat dibatalkan.
Kasus SEP Nokia
Kasus lain yang lebih kompleks adalah empat perkara antara Nokia Technologies Oy melawan beberapa pelaku industri perakitan dan penjualan ponsel di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan pola argumentasi SEP yang konsisten.
Nokia memetakan dua kelompok klaim Paten telekomunikasi ke dalam 3GPP Technical Specifications yang diadopsi dalam sistem standar Indonesia.
- Kelompok pertama membahas Paten 3G/UMTS terkait HSDPA 64QAM, yaitu teknologi yang mempercepat transfer data melalui teknik pengemasan yang lebih efisien. Nokia merujuk pada 3GPP TS 25.212, yang menjelaskan spesifikasi multiplexing dan channel coding dalam UMTS. Nokia berargumen bahwa ponsel yang patuh terhadap standar 3G ini secara otomatis menjalankan fitur-fitur yang telah dilindungi oleh klaim Paten mereka.
- Kelompok kedua berhubungan dengan Paten 4G, khususnya fitur yang diatur dalam 3GPP TS 36.212 (v8.8.0) mengenai multiplexing, channel coding, dan pemetaan ke saluran fisik pada E-UTRA (LTE). Paten ini mencakup metode penyampaian informasi konfigurasi antena berbasis bit mask, yang memungkinkan sinkronisasi antara perangkat pengguna (UE) dan base station untuk mempercepat transmisi data.
Nokia menjelaskan bahwa TS 36.212 v8.8.0 telah menjadi bagian dari standar global, termasuk di Indonesia. Dengan demikian, setiap ponsel yang beroperasi sesuai standar LTE kemungkinan besar menerapkan langkah-langkah teknis yang telah dipatenkan — dan karenanya memerlukan lisensi FRAND yang sah.
Keempat perkara tersebut mengacu pada definisi “Essential” menurut ETSI, yang menyatakan bahwa suatu Hak Kekayaan Intelektual dianggap esensial apabila, secara teknis, tidak mungkin membuat, menjual, atau mengoperasikan produk yang patuh terhadap standar tanpa melanggar hak tersebut.
Oleh karena itu, pemegang Paten wajib menyerahkan Pernyataan Informasi HKI dan Deklarasi Lisensi yang tidak dapat dibatalkan, serta bersedia melisensikan invensinya dengan syarat FRAND. Dengan mekanisme ini, hak eksklusif Paten tetap diakui, namun pelaksanaannya “dilunakkan” agar standar dapat diadopsi secara luas.
Dimensi Kontraktual dan Kelembagaan
Dimensi kontraktual internasional muncul melalui riwayat lisensi global dan lokal Nokia, yang digunakan untuk menunjukkan itikad baik FRAND dan praktik pasar yang non-diskriminatif. Sengketa biasanya muncul ketika lisensi berakhir dan negosiasi perpanjangan tidak mencapai kesepakatan, sehingga produk yang masih beredar menjadi “di luar lisensi”.
Pada titik ini, pertanyaan klasik SEP pun muncul:
- Apakah penawaran FRAND yang diajukan masih fair dan reasonable secara ekonomi?
- Apakah ada diskriminasi?
- Siapa pihak yang beritikad baik (willing/unwilling licensee)?
- Dan remedi apa yang proporsional — kompensasi finansial atau injunction?
Saksi ahli mengenai keharusan implementasi TS 36.212 bagi perangkat LTE memperkuat teori “pelanggaran melalui implementasi standar”, yang menjadi ciri khas sengketa SEP lintas negara.
Secara kelembagaan, 3GPP adalah proyek kolaborasi antara berbagai lembaga standardisasi dunia — ETSI di Eropa hanyalah salah satu mitra, bersama ATIS (AS), ARIB/TTC (Jepang), TTA (Korea), dan CCSA (Tiongkok). Karena itu, teknologi 3G/4G/5G merupakan hasil kontribusi banyak pihak, bukan milik tunggal satu pengembang.
ETSI menyediakan kebijakan HKI dan prosedur deklarasi, bukan sistem license pooling. Model lisensi yang lazim digunakan adalah lisensi bilateral berbasis FRAND, meskipun di beberapa sektor tersedia opsi lisensi melalui pool.
Bab Baru Diskursus SEP di Indonesia
Keempat perkara Nokia tersebut dapat dianggap sebagai bab pembuka litigasi SEP di Indonesia yang terdokumentasi secara publik. Penggugat menautkan klaim Paten ke nomor spesifik TS 3GPP, menegaskan deklarasi ETSI dan komitmen FRAND, lalu menghubungkannya dengan sertifikasi perangkat di pasar domestik sebagai dasar inferensi implementasi klaim.
Bagi pelaku industri, pelajarannya jelas: ketika teknologi privat “naik kelas” menjadi standar publik, hak Paten tetap ada — namun disertai kewajiban membuka akses melalui FRAND. Sebaliknya, pihak implementer memperoleh hak untuk mengakses standar, tetapi berkewajiban bernegosiasi dengan itikad baik untuk memperoleh lisensi yang layak.
Dalam era 5G dan Internet of Things (IoT), sengketa serupa sangat mungkin beririsan dengan hukum persaingan usaha dan koordinasi lintas yurisdiksi (termasuk isu anti-suit injunction). Karena itu, penting bagi pelaku industri untuk menyiapkan sejak awal pemetaan standar terhadap klaim, dokumentasi negosiasi, dan analisis kewajaran ekonomi sebagai bagian dari kepatuhan.
Menguji Esensialitas dan Kronologi
Dalam menilai perkara semacam ini, penting untuk tidak terjebak pada asumsi “otomatis esensial.” Seperti dicatat oleh Yi Yu et al. (2024), langkah awal pembelaan yang efektif adalah menguji apakah Paten yang disengketakan benar-benar esensial terhadap standar yang relevan, atau justru hanya mengatur fitur opsional yang belum tentu diimplementasikan.
Uji ini memerlukan pemetaan baris per baris antara elemen klaim dengan klausul standar yang bersifat wajib (mandatory conformance), serta verifikasi lapangan terhadap aktivasi fitur tersebut (misalnya dukungan 64QAM pada profil HSDPA tertentu, atau konfigurasi antena/MIMO yang memicu penggunaan bit mask khusus).
Apabila fitur yang dipetakan bersifat opsional atau dinonaktifkan pada varian tertentu, maka klaim “implementasi standar = implementasi klaim” menjadi lemah, dan beban pembuktian kembali berada pada pemegang SEP.
Selain itu, penting juga menelusuri kronologi integrasi standar: sejak versi berapa klausul standar yang dipetakan mulai berlaku. Perbedaan versi rilis 3GPP (misalnya TS 25.212 v7.12.0 untuk 3G dan TS 36.212 v8.8.0 untuk LTE) dapat memengaruhi apakah seluruh lini produk tergugat benar-benar berada dalam cakupan pada saat dipasarkan.
Relevansi Pasal 78 UU Paten dan Prinsip FRAND
Dari sisi kebijakan, Pasal 78 Undang-Undang Paten yang melarang klausul lisensi yang merugikan kepentingan nasional atau menghambat alih dan pengembangan teknologi, dapat dipandang sebagai dasar normatif penerapan prinsip FRAND di Indonesia.
Gagasan ini sejalan dengan pandangan Rani Nuradi (2023), yang menegaskan bahwa negara berkepentingan untuk menjamin akses yang adil terhadap teknologi yang telah menjadi standar, tanpa meniadakan hak eksklusif Paten.
Artinya, ketika suatu Paten diposisikan sebagai SEP, Pasal 78 memberi dasar hukum bagi otoritas atau pengadilan untuk menilai apakah struktur tarif, cakupan portofolio, atau kewajiban non-teknis (seperti bundling berlebihan atau cross-grant yang tidak proporsional) masih wajar dan tidak diskriminatif, atau justru merugikan kepentingan nasional karena menghambat difusi teknologi dan interoperabilitas.
Pelajaran dari Amerika Serikat dan Eropa
Di Amerika Serikat, kegagalan pemegang Paten mengungkap potensi esensialitas kepada SSO dapat berujung pada sanksi berat — mulai dari implied waiver atau equitable estoppel (paten tidak dapat ditegakkan terhadap pihak tertentu), pembatasan remedi hanya pada royalti, hingga temuan patent misuse.
Sementara di Uni Eropa, putusan terkenal Huawei v. ZTE menekankan pentingnya “ritual” negosiasi FRAND yang benar. Jika pemegang SEP langsung menuntut injunction tanpa melalui proses itu, mereka berisiko dianggap melakukan abuse of dominant position.
Dua pendekatan ini tidak perlu disalin mentah-mentah, tetapi memberikan kompas yuridis: bahwa esensialitas + keterbukaan (disclosure) + perilaku negosiasi adalah tiga simpul utama yang menentukan legitimasi penegakan SEP.
Masa Depan Litigasi SEP di Indonesia
Untuk konteks Indonesia, analisis dapat ditata secara berlapis:
- Filter Materiil (Pasal 78 UU Paten): Pengadilan dapat menilai dan menolak klausul lisensi yang “mencekik”, seperti tarif yang tidak seimbang dengan kontribusi standar di pasar lokal, atau kewajiban eksklusivitas yang menghambat TKDN dan transfer teknologi.
- Itikad Baik (Pasal 1338 KUHPerdata): Prinsip kepatutan memberi ruang bagi pengadilan untuk menilai perilaku negosiasi FRAND — apakah para pihak benar-benar willing atau justru melakukan penundaan strategis.
- Proporsionalitas Remedi: Dalam sengketa SEP, pengadilan sebaiknya memulai dari kompensasi atau royalti sebelum mempertimbangkan injunction, kecuali terdapat bukti kuat bahwa implementer tidak beritikad baik.
- Kewajiban Pengungkapan (Disclosure): Meskipun belum diatur secara eksplisit, kegagalan mengungkap hubungan antara invensi dan standar — apalagi jika disengaja — dapat dinilai sebagai penyalahgunaan hak yang melemahkan klaim untuk remedi berat.
Empat perkara Nokia dan kasus Polarchem menjadi titik awal yang penting dalam sejarah litigasi SEP di Indonesia. Ketika teknologi privat naik kelas menjadi standar publik, keseimbangan antara hak eksklusif dan akses yang adil menjadi kunci utama. Prinsip FRAND bukan sekadar kompromi, tetapi jembatan antara inovasi dan keterbukaan — antara kepemilikan dan interoperabilitas.
Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut terkait litigasi SEP dan Paten secara umum di Indonesia, hubungi kami melalui kanal berikut ini:
? E-Mail : [email protected]
? Book a Call : +62 21 83793812
? WhatsApp : +62 812 87000 889